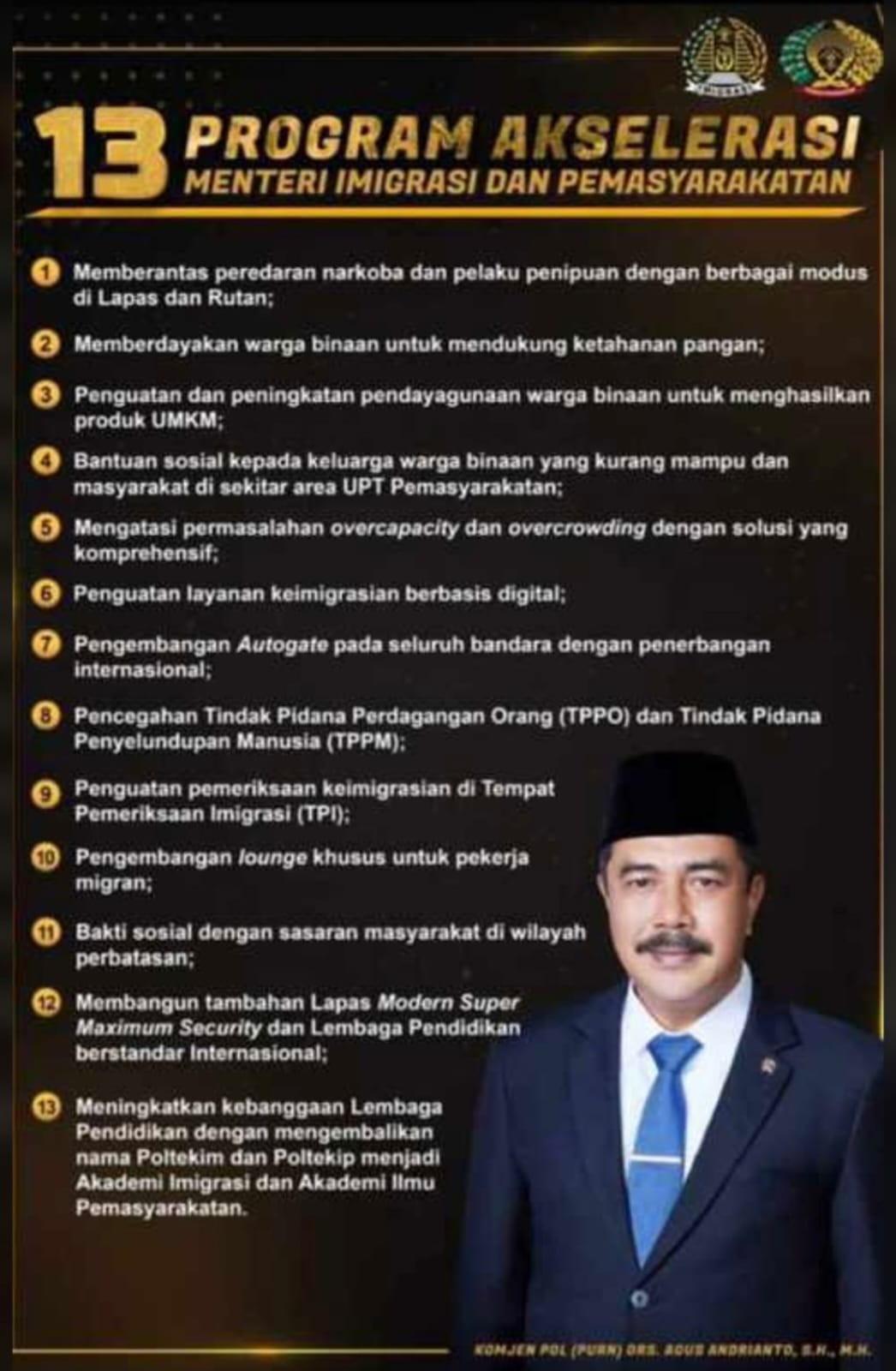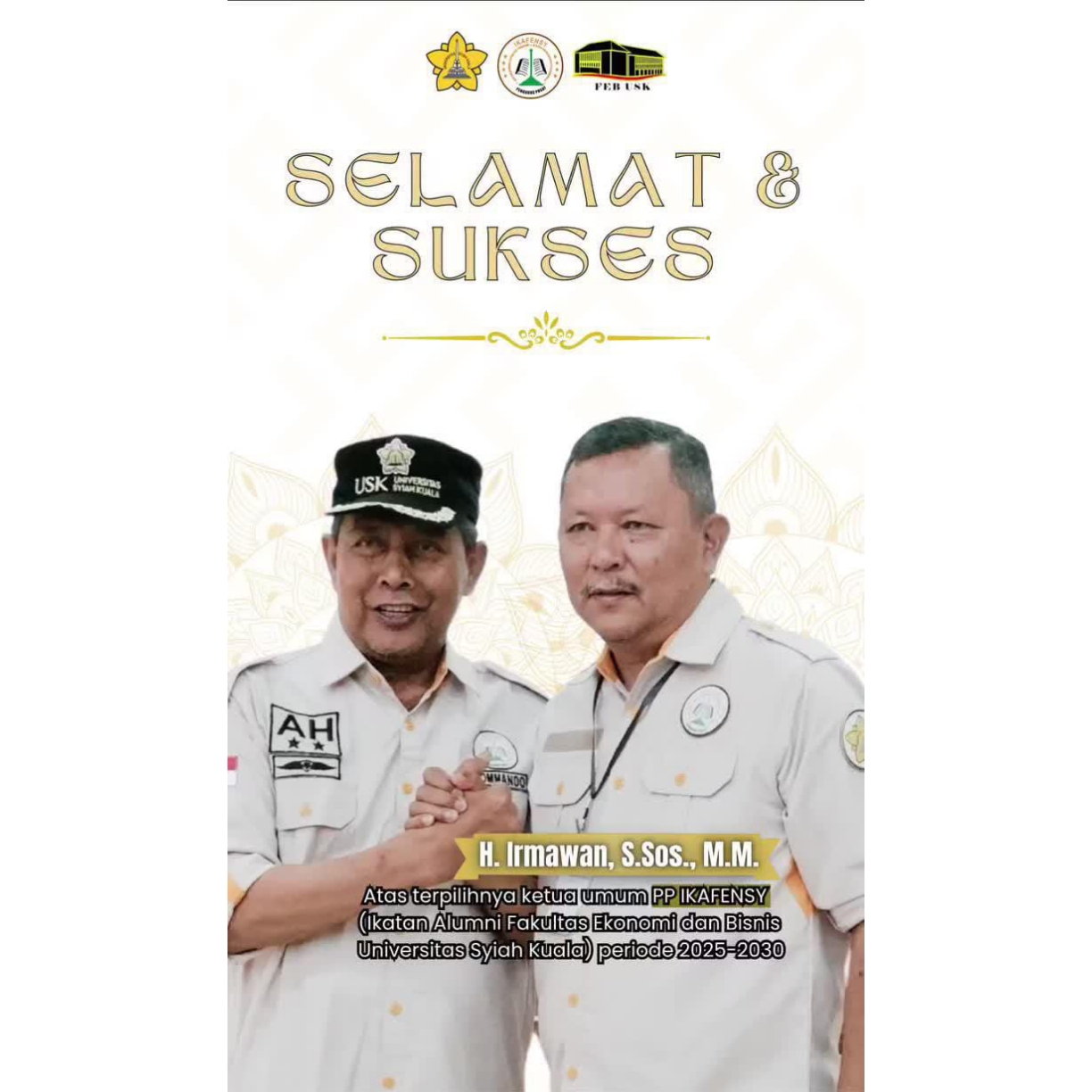PENYELESAIAN DAN PENANGANAN PERKARA PELANGGARAN HAM BERAT: MENCARI ALTERNATIF KEADILAN
Oleh : Erryl Prima Putera Agoes
Jaksa Ahli Utama Pada Jampidsus Kejagung RI
A. Pendahuluan
Pengaturan mengenai penyelesaian dan penanganan perkaran pelanggaran HAM Berat dari tahap penyelidikan hingga masuk ke tahap peradilan sebenarnya telah diatur di dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Karena hukumnya sudah ada dan berlaku, maka hukum tersebut harus dijunjung tinggi sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (the rule of law). Mengutip perspektif teori keadilan bermartabat yang telah disampaikan oleh Teguh Prasetyo bahwa karena hukum itu berdaulat maka hukum harus dijunjung tinggi tanpa keraguan. Namun dalam praktiknya, justru aparat Penyelidik (Komnas HAM) dan Penyidik (Kejaksaan Agung) saling meragukan kinerja satu sama lain. Secara normatif, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah memberikan wewenang kepada Komnas HAM sebagai komisi resmi negara yang berwenang melakukan penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya suatu peristiwa yang diduga pelanggaran HAM Berat, dan Jaksa Agung diberikan wewenang melalui Pasal 21 dan Pasal 23 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM untuk melakukan penyidikan dan penuntutan atas perkara pelanggaran HAM Berat berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM.
Sepanjang tahun 2002 hingga kini, masih terdapat 13 (tiga belas) berkas dugaan pelanggaran HAM Berat yang diajukan oleh Komnas HAM. Adapun 13 (tiga belas) berkas tersebut terdiri atas 9 (sembilan) berkas dugaan pelanggaran HAM Berat masa lalu dan 4 (empat) berkas dugaan pelanggaran HAM Berat masa kini. Terkait dengan 9 (sembilan) berkas dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu telah dilakukan bedah kasus di Hotel Novotel Bogor pada tanggal 15 hingga 19 Februari 2016 sebanyak 6 (enam) kasus yang difasilitasi oleh Menko Polhukam antara Penyelidik Komnas HAM dengan Penyidik Kejaksaan Agung dan didapat kesimpulan antara lain tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh karena pelaku tidak teridentifikasi dengan jelas; keterangan saksi berdiri sendiri; dan tidak terkonfirmasi dengan alat bukti lain; tidak ada visum et repertum; tidak ada ahli forensik; dan tidak ada dokumen yang membuktikan adanya perintah atau operasi. Kemudian, pernah terjadi kesepakatan antara penyelidik Komnas HAM dengan Penyidik namun ketika penandatanganan berita acara kesepakatan, Pimpinan Komnas HAM tidak berkenan menandatangi berita acara tersebut.
Sampai dengan saat ini terhadap ketiga belas berkas perkara yang diduga pelanggaran HAM Berat terjadi bolak balik berkas antara Penyidik (Kejaksaan) dengan Komnas HAM. Hal tersebut disebabkan perbedaan pendapat antara Penyelidik (Komnas HAM) dan Penyidik (Kejaksaan Agung). Menurut Kejaksaan Agung, hasil penyelidikan yang diberikan oleh Komnas HAM tidak memenuhi petunjuk Jaksa sebagaimana telah diuraikan di atas dengan argumentasi bahwa semuanya harus memenuhi unsur agar siap dilanjutkan ke tahap penyidikan dan peradilan guna menghindari putusan bebas dari majelis hakim sebagaimana preseden yang telah terjadi pada putusan perkara peristiwa Timor Timor tahun 1999, peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 dan Peristiwa Abepura tahun 1999. Sementara itu, Komnas HAM bersikeras berpendapat bahwa hasil penyeldikannya sudah cukup dan siap untuk lanjut ke tahap penyidikan. Alih-alih mengikuti petunjuk Kejaksaan Agung selaku Penyidik, Komnas HAM tidak menunjukan langkah-langkah yang kooperatif dan justru mengkomentari petunjuk Penyidik bahkan menuding Kejaksaan Agung menghambat proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat.
Bolak-balik berkas antara Komnas HAM dan Jaksa Agung telah berlangsung selama belasan tahun. Selama itu pula, bahkan lebih, jutaan korban pelanggaran HAM Berat terus mencari keadilan, kebenaran, reparasi, dan jaminan ketidakberulangan di masa depan. Jutaan keluarga korban masih mencari kepastian hukum mengenai nasib orang-ornag yang mereka kasihi, apa yang terjadi dan siapa yang bertanggungjawab atas peristiwa tersebut.
Berdasarkan fakta tersebut di atas, tulisan ini mengidentifikasi bagaimana problematika dalam penyelesaian dan penanganan kasus pelanggaran HAM Berat secara yuridis maupun non-yuridis, kemudian mengusulkan langkah-langkah alternatif yang dapat menyelesaikan kasus pelanggaran HAM Berat agar segera memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada korban serta keluarga korban.
B. Prinsip-Prinsip Internasional Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan bahwa dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia dalam rangka penghapusan impunitas harus meliputi keseluruhan aspek dan dimensi serta mekanisme yang mengedepankan empat pilar penting, yaitu hak untuk mengetahui kebenaran (right to know); hak atas keadilan (right to justice); hak atas reparasi (right to reparation); dan jaminan ketidakberulangan (guarantees of non-recurrence).[1]
- Hak untuk Mengetahui Kebenaran (Right to Know)
Pilar pertama ini memiliki beberapa prinsip umum, yaitu:
a. Hak atas Kebenaran yang Tidak Dapat Dicabut
Bahwa setiap orang memiliki hak yang tak dapat dicabut yaitu hak atas kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia, keadaan dan alasan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran yang meluas atau sistematis. Pemenuhan hak atas kebenaran secara menyeluruh akan dapat menjadi sebuah benteng vital bagi tidak terjadinya pelaggaran serupa.
b. Tugas Negara untuk Merawat Ingatan
Negara memiliki tugas untuk merawat arsip dan bukti-bukti dengan tujuan untuk merawat ingatan kolektif atas pelanggaran yang terjadi.
c. Hak Korban atas Kebenaran
Korban memiliki hak untuk tahu atas apa yang terjadi dan keadaan yang melingkupinya termasuk dengan nasib korban.
d. Jaminan Adanya Langkah Dilaksanakannya Hak atas Kebenaran
Negara harus mengambil langkah agar kebenaran dapat terwujud melalui langkah yudisial dan non-yudisial dimana keduanya saling melengkapi.
Prinsip ini juga memiliki prinsip penting lainnya, misalnya: Prinsip mengatur tentang pembentukan komisi untuk pengungkapan kebenaran, jaminan independensi, imparsialitas, dan kompetensi, masa kerja komisi, hak korba untuk memberi kesaksian, sumber daya yang cukup, serta publikasi laporan.
- Hak atas Keadilan (Right to Justice)
Pilar kedua memuat prinsip umum yaitu tugas negara untuk penyelidikan yang cepat, menyeluruh, independent dan juga imparsial atas pelanggaran hak asasi manusia dan mengambil langkah yang tapat berkaitan dengan pelaku yang diduga bertanggungjawab atas terjadinya suatu pelanggaran HAM Berat.
Pilar kedua juga memuat beberapa prinsip mendasar yaitu dibatasinya peradilan militer hanya untuk tindak pidana militer oleh personil militer yang dalam hal ini harus berada di bawah pengawasan peradilan umum. Prinsip ini juga memuat prinsip jaminan independensi hakim dan peradilan.
- Hak atas Reparasi (Right to Reparation)
Pilar ini memuat prinsip umum bahwa korban dan keluarga korban pelanggaran HAM Berat memiliki hak atas pemulihan. Hal ini memberi implikasi adanya kewajiban dan tugas negara untuk memberikan pemulihan kepada korban dan keluarganya serta upaya pemulihan dari pelaku. Dalam hal ini negara harus menjamin adanya prosedur bagi korban untuk menuntut pemulihan serta mempublikasikannya. Reparasi di sini harus mencakup restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.
- Jaminan Ketidakberulangan (Guarantees of Non-Recurrence)
Pilar ini menegaskan bahwa negara harus menjamin reformasi kelembagaan dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk menjamin adanya penghormatan terhadap the rule of law, mempercepat dan menjaga budaya penghormatan terhadap HAM serta membangun legitimasi publik terhadap negara.
C. Perkembangan Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran HAM Berat
Perkembangan terkini mengenai penuntasan pelanggaran HAM Berat, yaitu telah dibentuk Tim Khusus Penuntasan Dugaan Pelanggaran HAM Berat melalui Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: 263 Tahun 2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Pembentukan Tim Khusus Penuntasan Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat. Tim Khusus tersebut telah melakukan identifikasi, verifikasi dan upaya penuntasan terhadap 9 (sembilan) berkas hasil penyelidikan Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM Berat masa lalu. Pada 2 Maret 2021, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan mengundang Tim Khusus untuk melakukan pemaparan hasil kerja Tim Khusus Penuntasan Dugaan Peristiwa Pelanggaran HAM Berat di hadapan Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan, dengan kesimpulan:
- 9 (sembilan) hasil penyelidikan Komnas HAM belum memenuhi syarat formil dan materiil untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan dalam rangka pemenuhan syarat formil dan materiil berkas hasil penyelidikan Komnas HAM belum dipenuhi oleh Penyelidik Komnas HAM;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengandung beberapa kelemahan yang menghambat penuntasan pelanggaran HAM Berat.
Lebih lanjut, pada 31 Mei 2021 Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan mengundang Kejaksaan (Timsus) dan Komnas HAM untuk rapat koordinasi pembahasan penyelesaian dugaan pelanggaran HAM berat hasil penyelidikan Komnas HAM dengan kesimpulan:
- Penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat secara yudisial bisa dilakukan dengan cara penyelidikan Komnas HAM memenuhi petunjuk Jaksa Agung;
- Penyelesaian secara non yudisial bisa dilakukan dengan pengajuan rencana peraturan Presiden yang materiilnya adalah perbaikan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU/IV/2006.
Menindaklanjuti hasil rapat pada 31 Mei 2021 tersebut, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menerbitkan Surat Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Nomor: B-78/HK.00.03/06/2021 tanggal 9 Juni 2021, perihal mendorong proses penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang berat secara Yudisial yang ditujukan ke Komnas HAM. Yang pada pokoknya inti surat adalah “meminta Komnas HAM untuk memenuhi petunjuk Jaksa Agung”.
D. Problematika Dalam Penyelesaian dan Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat
- Problematika Secara Yudisial
UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur beberapa ketentuan penting. Pertama, mengenai yurisdiksi Pengadilan HAM, yaitu pelanggaran HAM yang berat mencakup Kejahatan Genosida, dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Kedua, mengatur tentang pertanggung jawaban komandan dan pertanggungjawaban polisi atau atasan sipil lainnya. Perlunya pembentukan UU Pengadilan HAM secara khusus di luar pengaturan peradilan pidana umum menunjukan adanya kesadaran pembentuk undang-undang bahwa penanganan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida ini adalah kejahatan luar biasa yang tidak dapat ditangani dengan sistem peradilan pidana biasa. Pengaturan yang sifatnya khusus ini didasarkan atas kerakteristik kejahatan yang sifatnya extraordinary sehingga memerlukan pengaturan dan mekanisme yang juga sifatnya khusus. Pengaturan khusus yang diatur oleh UU Pengadilan HAM dapat dilihat sejak tahap penyelidikan dimana yang berwenang adalah Komnas Ham sampai pengaturan tentang majelis hakim dimana komposisinya berbeda dengan pengadilan pidana biasa. Meskipun begitu, hukum acara yang digunakan masih menggunakan hukum acara pidana terutama prosedur pembuktiannya.[2]
Permasalahan selanjutnya pada UU Pengadilan HAM, yaitu rumitnya birokrasi pembentukan Pengadilan HAM ad hoc. Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc harus dibentuk melalui Keputusan Presiden atas usul DPR berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM dan hasil penyidikan Jaksa Agung.[3] Selain rumitnya birokrasi, biasnya pengaturan tentang pembentukan Pengadilan HAM ad hoc tersebut sebelum adanya Putusan MK No. 18/PUU-V/2007 menimbulkan dualisme penyelidikan seperti halnya Komnas HAM pernah membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM (KPP HAM) untuk kasus Trisakti dan Semanggi pada 5 Juni 2001, sementara DPR yang membentuk Panitia Khusus yang menentukan bahwa kasus Trisakti dan Semanggi bukan merupakan pelanggaran HAM Berat pada 28 Juni 2001. Dalam perkembangannya, Putusan MK No. 18/PUU-V/2007 menghapuskan frasa “dugaan” pada Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM sehingga menegaskan kepada DPR bahwa otoritasnya memberikan usul tidak serta merta menduga sendiri, melainkan harus berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM dan hasil penyidikan Jaksa Agung. Meskipun begitu, kewenangan DPR untuk memberikan usul pembentukan Pengadilan HAM ad hoc merupakan suatu hal yang bersifat politis. Pengambilan kebijakan untuk menentukan apakah suatu kasus dapat dikatakan suatu pelanggaran HAM Berat atau tidak, seharusnya dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan disertai dengan menjunjung tinggi independensi, imparsialitas dan menghindari segala hal yang bersifat politis agar segera memberikan kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan bagi para korban dan keluarga korban.
Kelemahan lainnya adalah, lemahnya pengaturan terkait pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi pada Pasal 35 UU Pengadilan HAM dan PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompnesasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat. Di dalam pengaturan tersebut mesyaratkan bahwa kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi tercantum di dalam amar Putusan Pengadilan HAM. Sehingga mengakibatkan pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada korban dan keluarga korban menjadi terhambat. Konsekuensi atas lemahnya rumusan ketentuan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi ini pada akhirnya akan merugikan korban dan hal ini terbukti misalnya pada putusan Pengadilan HAM ad hoc kasus Tanjung Priok yang pada tingkat pertama korban diberikan kompensasi namun dengan bebasnya terdakwa, tidak ada kejelasan terkait kompensasi tersebut.
Selain itu, peraturan tersebut juga tidak menjelaskan secara detail mengenai besaran jumlah kompensasi sehingga indikator cara penghitungan pemberian kompensasi kepada korban dan kelaurga korban menjadi tidak jelas. Pada kasus Tanjung Priok, Majelis Hakim menyatakan bahwa kompensasi akan diberikan kepada korban dan ahli warisnya yang proses serta jumlahnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rumusan putusan ini membingungkan karena kewenangan mengenai jumlah atau besarnya ganti kerugian adalah sepenuhnya kewanangan majelis hakim, sementara majelis hakim malah menunjuk besar jumlah kompensasi kepada peraturan yang berlaku padahal hingga saat ini tidak ada peraturan mengenai bagaimana menghitung jumlah kompensasi dalam kasus-kasus pelanggaran HAM Berat.
- Problematika Secara Non-Yudisial
Pada dasarnya, UU Pengadilan HAM telah mengatur penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat baik secara yudisial maupun non-yudisial. Sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 47 UU Pengadilan HAM bahwa (1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; (2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang.
Menindaklanjuti Pasal 47 UU Pengadilan HAM tersebut, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang selanjutnya disebut KKR, dibentuk melalui UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Namun, UU tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945 oleh MK melalui Putusan No. 006/PUU-IV/2006. MK menilai bahwa rumusan norma di dalam UU No. 27 Tahun 2004 tidak memiliki kepastian hukum, sehingga UU tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Meskipun demikian, di dalam putusan tersebut MK menegaskan bahwa penilaian terhadap UU No. 27 Tahun 2004 tersebut tidak berarti MK menutup upaya penyelesaian pelanggaran HAM Berat di masa lalu melalui rekonsiliasi. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk itu, antara lain dengan mewujudkan rekonsiliasi dalam bentuk kebijakan hukum (undang-undang) yang serasi dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal.
E. Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat
Dari berbagai persoalan yang dihadapi dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, ada beberapa alternatif yang mungkin dapat digunakan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat agar para korban dan keluarga korban segera mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan.
- Mendorong Presiden agar menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada UU Pengadilan HAM dan mengakomodasi Revisi UU KKR
Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam sistem norma hukum negara Republik Indonesia. Perppu dikonsepsikan sebagai suatu peraturan yang dari segi isinya seharusnya ditetapkan dalam bentuk undang-undang, tetapi karena keadaan kegentingan memaksa ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah. Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) disebutkan bahwa “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Jika mengacu pada rumusan ini maka jelaslah bahwa sejatinya Perppu merupakan suatu peraturan pemerintah, namun berfungsi sebagai undang-undang. Dengan demikian Perppu merupakan salah satu instrumen hukum yang dapat ditetapkan oleh Presiden tanpa memerlukan keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meskipun begitu, Perppu tetap harus mendapatkan persetujuan dari DPR pada persidangan DPR yang terdekat. Jika suatu Perppu disetujui oleh DPR, maka Perppu tersebut disahkan menjadi undang-undang. Sedangkan jika suatu Perppu ditolak oleh DPR maka Perppu tersebut harus dicabut.
Hal yang selalu menjadi kontroversi hingga saat ini adalah ukuran mengenai “kegentingan yang memaksa” sebagai dasar politis dan sosiologis bagi pembentukan Perppu. Bahkan seringkali muncul pameo di masyarakat bahwa Perppu umumnya dibentuk bukan karena adanya kegentingan yang memaksa, melainkan karena adanya kepentingan yang memaksa. Dalam teori-teori yang berkaitan dengan hukum tata negara darurat, disebutkan bahwa “kegentingan yang memaksa” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 UUD Tahun 1945 lebih menekankan pada aspek kebutuhan hukum yang bersifat mendesak atau urgensi yang terkait dengan waktu yang terbatas. Setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur penting yang dapat menimbulkan suatu “kegentingan yang memaksa”, yakni unsur ancaman yang membahayakan (dangerous threat); unsur kebutuhan yang mengharuskan (reasonable necessity); dan/atau unsur keterbatasan waktu (limited time) yang tersedia. Berdasarkan ketiga usur tersebut, apabila kasus pelanggaran HAM Berat belum terselesaikan maka dapat memenuhi ketiga unsur tersebut. Jika penyelesaian pelanggaran HAM Berat tidak mendapatkan kepastian hukum, maka akan mereduksi budaya penghormatan terhadap HAM dan negara berpotensi tidak aman bagi masyarakat karena tidak mampu memberikan perlindungan hukum yang jelas.
Perlunya Perppu dalam hal ini untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada di dalam UU Pengadilan HAM, misalnya Jaksa Agung dan Komnas HAM diberikan panduan yang jelas terkait proses penyelidikan dan penyidikan atau memberikan kelonggaran kepada Komnas HAM dan Jaksa Agung agar dapat membentuk tim gabungan agar proses penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM dapat sesuai dengan arahan dari Jaksa Agung. Kerja sama antara Komnas HAM dan Jaksa Agung di sini merupakan jantung dari penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat. Para Korban dan keluarganya menaruh harapan lebih dari satu dekade akibat ketidaksinkronan antara kinerja Komnas HAM dan Jaksa Agung dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat.
Kemudian, terkait rekonsiliasi, restitusi dan rehabilitasi yang pengaturannya sangat lemah pada UU Pengadilan HAM juga UU KKR yang dinyatakan inkonstitusional oleh MK, maka dengan adanya penerbitan Perppu diharapkan untuk mengakomodasi semua permasalahan tersebut. Dengan melihat kondisi penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat melalui jalur yudisial terhambat oleh sejumlah hambatan, bahkan korban dan mungkin terduga pelakunya sudah meninggal dunia, maka alternatif lainnya adalah melalui rekonsiliasi. Sebagaimana yang ditegaskan oleh MK bahwa tidak menutup kemungkinan untuk melakukan upaya rekonsiliasi, sepanjang pengaturan terkait pembentukan KKR sesuai dengan Konstitusi. Pada dasarnya, KKR merupakan mekanisme alternative dispute resolution, yang akan menyelesaikan suatu permasalahan HAM secara amicable karena tidak dimungkinkan penyelesaian melalui jalur yudisial. Ketertutupan proses hukum melalui Pengadilan HAM ad hoc apabila memperoleh penyelesaian di KKR adalah akibat yang logis dari satu mekanisme alternative dispute resolution sehingga tidak perlu dilihat sebagai pembenaran impunitas. Karena, dengan mekanisme hukum terhadap pelanggaran HAM Berat masa lalu telah mengalami kesukaran dengan berlalunya jangka waktu yang lama yang menyebabkan hilangnya alat-alat bukti untuk dijadikan dasar pembuktian dalam pendekatan individual criminal responsibility.
Sebagai panduan bagaimana restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi kepada para korban dan keluarga korban kasus pelanggaran HAM Berat, Resolusi Majelis Umum PBB No. 60/147 menghasilkan Prinsip-Prinsip Dasar dan Panduan untuk Hak atas Penyelesaian (Right to Remedy) dan Reparasi untuk Korban Pelanggaran yang Berat atas Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Pelanggaran HAM yang Berat atas Hukum Humaniter Internasional, pada paragraf 19-22 Resolusi tersebut menyebutkan bahwa:
-
- Restitusi harus (jika memungkinkan) mengembalikan korban pada situasi semula sebelum pelanggaran HAM Berat. Restitusi meliputi restorasi kebebasan, pemenuhan HAM (hak identitas, hak kehidupan berkeluarga, hak kembali ke tempat tinggal asalnya, restorasi ketenagakerjaan dan pengembalian properti).
- Kompensasi harus diberikan untuk kerusakan yang dapat dinilai secara ekonomi, sejauh diperlukan dan proporsional dengan beratnya pelanggaran dan kondisi masing-masing kasus, sebagai akibat dari pelanggaran HAM Berat, seperti kerusakan fisik atau mental; hilangnya kesempatan termasuk pekerjaan, pendidikan, dan manfaat sosial; kerugian-kerugian dan hilangnya pendapatan; kerusakan moral; biaya-biaya yang diperlukan untuk bantuan hukum atau ahli, pelayanan pengobatan medis dan bantuan psikologis.
- Rehabilitasi harus meliputi perawatan medis dan psikologis serta bantuan hukum dan sosial.
- Menjalin komunikasi dan diskusi secara terbuka baik antar lembaga negara maupun dengan para korban dan keluarga korban serta organisasi masyarakat sipil yang fokus terhadap penyelesaian pelanggaran HAM Berat.
Sudah satu dekade lebih penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat belum terselesaikan, wajar saja apabila terjadi delegitimasi publik terhadap komitmen negara dalam pemenuhan dan penghormatan HAM. Oleh karena itu, untuk mengurangi pandangan-pandangan bias dari masyarakat sipil maka Komnas HAM dan Jaksa Agung dapat melakukan diskusi secara terbuka (seperti FGD atau bentuk lainnya) terkait permasalahan yang sedang dihadapi dan sejauh mana proses yang telah dilakukan. Diskusi yang terbuka dengan organisasi masyarakat sipil juga akan sangat membantu karena mereka berhubungan dekat dengan para korban dan keluarga korban, dimana apabila suara-suara korban dan keluarga korban belum tersampaikan dapat disampaikan oleh organisasi masyarakat sipil tersebut. Suara-suara korban dan keluarga korban sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kompensasi yang harus diberikan atas terjadinya pelanggaran HAM Berat.
Selain itu, permintaan maaf negara melalui Presiden atas terjadinya pelanggaran HAM Berat dan lambatnya proses penyelesaian kepada para korban dan keluarga korban juga diperlukan. Untuk permintaan maaf perlu dikaji lebih lanjut permintaan maaf yang dimaksud menyangkut aspek apa saja, dan tentunya negara juga berjanji bahwa peristiwa pelanggaran HAM Berat tidak akan terulang di masa mendatang.
F. Penutup
Apapun langkah penyelesaian yang ditempuh, sepanjang untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada para korban sekaligus mengungkapkan kebenaran atas peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Upaya penyelesaian yang ditempuh juga harus mengutamakan pemenuhan hak-hak para korban.
Catatan kaki
[1] Diane Orentlicher, E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 February 2005, Report of The Independent Expert to Update the Set of Principles to Combat Impunity, Commission on Human Rights Sixty-First Session, UN Commission on Human Rights.
[2] Pasal 10 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
[3] Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Jo. Putusan MK No. 18/PUU-V/2007.